Perjuangan Kartini Lebih Dari Sekedar Kebaya dan Diskon Berbagai Rupa
- Apr 21, 2018
-
 Fildza Hasna
Fildza Hasna
Raden Adjeng Kartini, atau R.A Kartini lahir pada suatu hari di tanggal 21 April 1879. Gadis kecil yang tumbuh di kalangan keluarga bangsawan jawa ini memiliki minat yang besar di bidang pendidikan, dan memilih untuk menghabiskan waktu senggangnya membaca buku, menulis, atau berkirim surat dengan sahabat-sahabat penanya.
Siapa sangka, perempuan yang memiliki nama panggilan Trinil ini akan tumbuh besar menjadi salah satu pahlawan negara yang namanya harum hingga kini. Mulai dari lagu nasional hingga hari peringatan, sosok R.A Kartini telah mempengaruhi banyak aspek sejarah negeri ini—khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
Saya ingat dulu waktu masih TK, pada tanggal 21 April sekolah kerap memberikan himbauan bagi siswa perempuan untuk mengenakan kebaya atau ragam jenis pakaian adat lainnya. Rupanya, tradisi ini berlanjut hingga jenjang sekolah berikutnya, dan bahkan bagi beberapa kawan saya, hingga di tempat kerja mereka.
Kebaya dan Hari Kartini telah melekat dengan satu sama lain selayaknya Lebaran dengan ketupat dan opor ayam. Hari kelahiran tokoh nasional pergerakan perempuan itu kini identik dengan parade kebaya berwarna cantik, perlombaan bertema ‘perempuan’ (seperti lomba memasak nasi goreng misalnya), dan promo menarik untuk para ‘Kartini Modern’ dari berbagai macam toko online, restoran, dan pusat perbelanjaan.
Tapi, apakah makna perjuangan seorang Kartini hanya sampai di situ aja?
Perjuangan yang Lebih dari Sekedar Kebaya
Apa sih yang diperjuangkan oleh seorang R.A. Kartini?
Pertanyaan ini mungkin bisa dengan mudah dijawab oleh kamu atau anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan, hak perempuan untuk dapat dipandang setara di masyarakat, hak perempuan untuk mendapat pendidikan yang layak.
Lahir dari keluarga bangsawan, R.A. Kartini memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah Eropa, Europee Lagere School (ELS), di mana ia antara lain belajar Bahasa Belanda. Sayangnya, status kebangsawanan Kartini nggak cukup untuk membuatnya mendapatkan ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Pada umur 12 tahun, Kartini terpaksa menyudahi pendidikannya untuk tinggal di rumah dan dipingit.
In case kamu nggak tau, dulu untuk bisa bersekolah itu adalah sebuah kemewahan bagi perempuan, khususnya perempuan pribumi. Sekolah-sekolah yang didirikan untuk pribumi kala itu masih sedikit yang menerima perempuan sebagai muridnya, itupun hanya terbatas pada perempuan-perempuan dengan darah bangsawan. Perempuan dianggap nggak butuh ilmu tinggi-tinggi karena tugas mereka hanyalah menjadi istri dari seorang laki-laki dan menjadi ibu untuk anak-anaknya.
Kartini yang kala itu merasa haknya direnggut paksa pun bercerita mengenai masalah ini kepada teman-teman penanya di Belanda. Berbekal pengetahuan Bahasa Belanda yang didapatkan di ELS, Kartini memulai rangkaian surat menyuratnya dengan beberapa sahabat pena seperti Estella H Zeehandelaar, Nyonya Ovink-Soer, Nyonya RM Abendanon-Mandri, Tuan Prof. Dr. GK Anton beserta Nyonya Hilda G de Booij, dan Nyonya van Kol.
Dari rangkaian surat menyurat inilah timbul keinginan Kartini untuk mengubah keadaan. Ia yang kala itu telah banyak membaca buku, koran, serta majalah Eropa mulai tertarik untuk mendalami pemikiran-pemikiran modern perempuan di Eropa. Beberapa kali Kartini bahkan sempat mengirimkan tulisannya sendiri ke sebuah majalah perempuan Belanda, De Hollandsche Lelie. Kartini menentang keras budaya yang menganggap perempuan memiliki derajat lebih rendah dari laki-laki, dan juga mengkritisi kesenjangan sosial yang terjadi antara kaum bangsawan dan rakyat kecil di lingkungan tempatnya berada. Kartini menginginkan perubahan, dan ia menginginkan perubahan tersebut terjadi melalui suatu jalur yang sudah selayaknya menjadi hak sleuruh lapisan masyarakat; pendidikan.
Dalam buku The Chronicle of Kartini karya Wiwid Prasetyo, Kartini mengatakan, “Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk mengubah pola pikir mereka, yakni penanaman kesadaran bahwa saat ini mereka tertindas, tanpa pendidikan mereka akan terus terjajah dan tidak menyadari bahwa diri mereka sebenarnya terbelenggu.”
Kalau Kartini hidup di zaman sekarang, mungkin label ‘feminis’ telah melekat erat pada dirinya. Tapi, pada zamannya dulu istilah tersebut belum populer, bahkan belum diketahui masyarakat luas. Seorang Kartini nggak bergerak untuk memberikan pendidikan yang setara bagi perempuan dan rakyat miskin hanya untuk mendapat pengakuan sebagai feminis dari orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ia malah lebih sering mendapat penentangan karena aksinya kala itu dianggap berlawanan dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang masih sangat patriarkis.
Kartini memperjuangkan hak perempuan dan rakyat miskin bukan untuk pujian atau popularitas. Ia memperjuangkan hal tersebut semata-mata karena ia melihat pendidikan sebagai alat pembebasan. Pembebasan dari penjajahan, pembebasan dari kemiskinan, dan pembebasan dari belenggu penindasan.
Kalau dipikir-pikir lagi, sayang banget nggak sih kalau sekarang kita hanya ‘merayakan’ perjuangan ini hanya dengan parade kebaya dan lomba memasak nasi goreng—tanpa memahami makna sesungguhnya dari apa yang diperjuangkan Kartini?
Pendidikan, Perempuan, dan Masalah yang Belum Terselesaikan
Beberapa hari yang lalu, sebuah berita mengenai guru-guru di Papua yang disandra oleh kelompok separatis menguak ke permukaan. 18 guru yang mengajar di sebuah sekolah dasar di daerah Aroanop dan Jagamin itu mengalami penyanderaan pada hari Jumat (13/4) pada pukul 15:00 WIT. Mereka ditangkap, disiksa, dan bahkan mengalami kekerasan seksual selama periode penyanderaan. Beruntung pada Kamis (19/4) 13 dari 18 guru tersebut telah berhasil dievakuasi oleh TNI, sementara sisanya masih berada di kampung yang terletak pada distrik Tembagapura itu, menunggu evakuasi lanjutan.
Gaes, cerita di atas merupakan contoh potret pendidikan di negara kita tercinta. Saat kalian-kalian yang ada di kota besar bisa dengan mudah mengakses pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, di daerah terpencil sana untuk sekolah aja mereka harus menghadapi resiko hidup dan mati layaknya para guru yang jadi korban penyanderaan tersebut. Belum lagi soal sarana dan prasarana yang sangat jauh dari kata memadai, plus minimnya akses terhadap teknologi informasi. Kalau pembahasan ini dilanjutkan, mungkin saya bisa membuat satu novel sendiri.
Permasalahan pendidikan di negeri ini nyatanya nggak hanya sebatas sistem Ujian Nasional dan seleksi masuk PTN yang tiba-tiba berganti, ya?
Itu baru ngomongin dunia pendidikan secara umum, lho. Kalau ngomongin pendidikan dan perempuan, masalah yang ada akan bertambah jumlahnya.
Kalian pernah nggak mendengar selentingan yang berbunyi: “Jadi cewek mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar ujung-ujungnya juga harus nurut sama suami”? Kedengarannya seperti masalah yang klise dan so last decade banget, ya. Hari gini cewek masih ‘dilarang’ buat sekolah tinggi-tinggi? Ya kali.
Tapi tau nggak gaes, menurut data dari Mendikbud sebanyak dua per tiga dari total 3,4 juta penduduk buta huruf adalah kaum perempuan. Bayangin, di zamannya kemajuan teknologi begini, Indonesia masih harus menghadapi masalah mendasar dari dunia pendidikan yaitu buta aksara. Yang lebih menyedihkan lagi, perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap masalah ini.
Faktanya, masih banyak lho anak-anak perempuan di pedesaan yang nggak bisa atau bahkan dilarang untuk bersekolah tinggi-tinggi hanya karena ia adalah perempuan. Seperti yang sudah sempat disinggung di atas, perempuan kerap masih dianggap sebagai ‘pengurus rumah’ belaka yang tanggung jawab utamanya adalah mengurus dapur, anak, dan suami. Mau setinggi apapun mereka bercita-cita, bagi sebagian masyarakat tempat mereka tetaplah di ranah domestik.
Sedih rasanya kalau ngomongin ini sambil mengingat-ingat perjuangan Kartini. Sudah lewat satu abad, tapi masalahnya masih aja berputar-putar di situ. Huft.
Seharusnya Hari Kartini bisa dijadikan sebagai alarm tahunan akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan Indonsia, khususnya di bidang pendidikan. Semangatnya memperjuangkan kesetaraan hak dan kelas sosial sudah sepatutnya direplikasi oleh kamu dan segenap Kartini-Kartini masa kini lainnya.
Hari lahir salah satu pahlawan perempuan ternama di Indonesia ini harusnya jangan cuma dikomersialisasi dalam bentuk promo dan diskon beragam rupa, tapi juga dijadikan momentum membakar lagi api perjuangan sang Raden Adjeng dalam menciptakan kesetaraan gender dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apalah artinya diskon kalau untuk pendidikan yang layak aja, masih banyak perempuan yang belum bisa menikmatinya.
Ya nggak?
Baca juga:
- Tentang Hari Perempuan Internasional dan Perjuangan yang Masih Harus Dilanjutkan
- Ketika ‘Cantik’ Bukan Lagi Pujian, dan Ruang Publik Tak Lagi Aman Untuk Perempuan
- Tentang Sebuah Siku Misterius di Majalah Time Edisi Person of The Year
- Infografik: Perempuan, Teknologi, dan Harapan Bagi Masa Depan
Kategori
 Hak Cipta Dilindungi 2015 - 2026 PT Manual Muda Indonesia ©
Hak Cipta Dilindungi 2015 - 2026 PT Manual Muda Indonesia ©

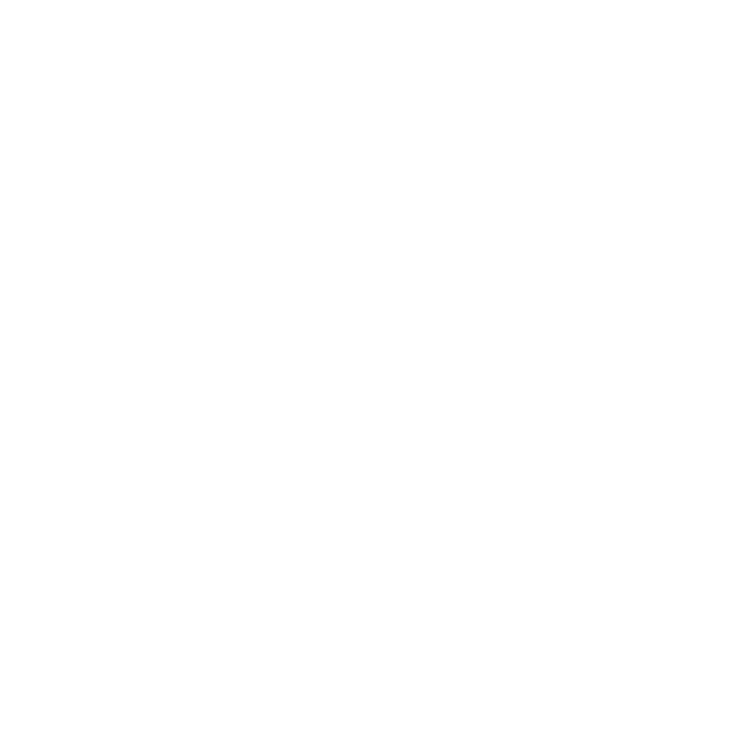





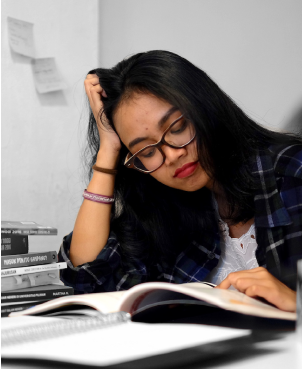


Anda bisa berbicara dengan call center Batik Air 0838~0015~0086 atau melalui WhatsApp 0838~0015~0086 untuk bantuan reschedule dan refund
Info Penerimaan Mahasiswa ITPLN 2022: Ada 3 Prodi Baru!Layanan Bantuan Pelanggan 24 Jam Hubungi Atau WhatsApp Cs Agoda 0858-1153-3912
Info Penerimaan Mahasiswa ITPLN 2022: Ada 3 Prodi Baru!I recently decided to try something new and came across bitcoin online casinos https://casinohex.jp/online-casinos/bitcoin-casinos/. I've been interested in cryptocurrency for a long time, but I didn't think it would work so well in casinos. Deposits take seconds, and withdrawals are instant.…
Industri Game Makin Menjanjikan, Inilah Pilihan Profesi Untuk Para Pecinta GameYuk teman-teman bisa dibaca artikel dibawah ini yang merasa stress saat kuliah https://s1kebidanan.fk.unesa.ac.id/post/tips-kuliah-tanpa-stres-bisa-kok
7 Tips Ampuh Hadapi Tugas Kuliah yang Numpuk Biar Kamu Tak Merasa StressWow, this hobby is pretty cool! If you're interested in reading about other fun hobbies, check it out here: https://hobiapaaja01.wordpress.com
10 Hobi yang Mencerminkan Kepribadianmu